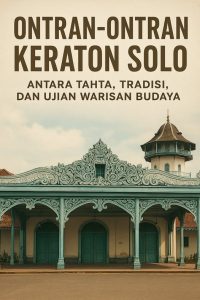
Solo(JARINGAN ARWIRA MEDIA GROUP)- Ada yang bergolak di balik dinding megah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bukan bunyi gamelan atau tabuh kendang, melainkan gema ontran-ontran— istilah khas Jawa yang menggambarkan hiruk-pikuk, konflik, atau kegaduhan di dalam rumah sendiri. Kali ini, sumber riuh itu bukan dari rakyat, melainkan dari keluarga besar pewaris tahta kerajaan Mataram yang kini tengah memperebutkan satu hal paling simbolik: mahkota kebesaran.
Sejak wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada awal November 2025, bara lama yang sempat meredup kembali menyala. Dua putra raja — KGPH Hangabehi dan KGPH Purbaya — kini sama-sama mengklaim diri sebagai penerus sah tahta Keraton Surakarta. Keduanya mengantongi dukungan dari kelompok internal yang berbeda, dari sentana dalem hingga abdi keraton. Dan seperti lazimnya perebutan kekuasaan, ketika simbol kebangsawanan beradu dengan ambisi pribadi, sejarah pun kembali menulis dirinya dengan tinta panas.
Tahta yang Tak Pernah Sepi
Keraton Surakarta bukan sekadar bangunan bersejarah. Ia adalah simbol identitas kultural Jawa yang hidup — rumah dari tradisi, filosofi, dan warisan leluhur Mataram Islam. Namun, di balik kebesaran itu, sejarahnya juga tak luput dari retakan. Sejak tahun 2004, Keraton Solo telah mengalami perpecahan internal antara dua kubu utama: pihak Hangabehi dan pihak Tedjowulan (adik almarhum PB XIII). Konflik ini meninggalkan luka panjang hingga akhirnya PB XIII (Hanggabehi) diakui sebagai raja tunggal oleh negara.
Kini, situasi serupa muncul kembali, hanya dengan wajah baru: Purbaya di satu sisi, Hanggabehi di sisi lain. Seakan sejarah menulis ulang dirinya sendiri — perbedaan tafsir atas siapa pewaris sah tahta kembali memicu gesekan antara adat dan ambisi.
Dalam konteks ini, ontran-ontran bukan hanya soal siapa yang akan duduk di singgasana, tetapi juga siapa yang berhak mendefinisikan makna keraton itu sendiri di era modern.
Ketika Warisan Bertemu Ego
Kedua pihak tentu memiliki argumentasi. Kubu Hanggabehi, sebagai putra tertua PB XIII, menganggap suksesi otomatis jatuh padanya — berdasar garis keturunan dan legitimasi adat. Sementara Purbaya, yang lebih muda, didukung sebagian besar struktur adat dan lembaga dalam keraton yang menilai bahwa suksesi harus melalui rembug keluarga besar, bukan otomatis berdasar usia.
Di titik inilah, warisan budaya bertemu dengan ego personal. Keraton, yang sejatinya menjadi simbol kebijaksanaan dan keselarasan, justru tampak terjebak dalam logika modern: legalitas, gugatan pengadilan, bahkan klaim di media. Padahal, esensi dari institusi seperti ini adalah pitutur luhur — kearifan yang memuliakan dialog dan keseimbangan.
Namun faktanya, politik simbolik kini telah masuk ke ruang budaya. Tahta, meski tak lagi punya kekuasaan politik formal, tetap memiliki nilai legitimasi sosial yang tinggi. Ia bisa menjadi pintu menuju pengaruh, prestise, bahkan sumber ekonomi.
Warisan yang Terguncang
Dampak ontran-ontran ini tak bisa diremehkan. Bagi masyarakat Jawa, Keraton Surakarta bukan sekadar situs budaya, tetapi juga penjaga spiritual, penggerak seni, dan penuntun moral masyarakat. Ketika para pewarisnya berselisih, gema kegaduhan itu terasa hingga ke luar tembok keraton — ke hati rakyat yang selama ini menghormatinya.
Di sisi lain, konflik ini juga menjadi refleksi besar bagi bangsa kita: seberapa siap kita menjaga warisan tradisional di tengah modernitas yang serba cepat dan legalistik? Bagaimana adat yang bersumber dari nilai kawruh Jawa bisa bertahan di tengah tekanan hukum positif dan opini publik digital yang sering kali memanas di media sosial?
Keraton Surakarta seharusnya menjadi teladan kebijaksanaan, bukan arena perebutan. Jika kisruh ini terus berlarut, bukan tak mungkin generasi muda akan kehilangan hormat terhadap simbol-simbol budaya sendiri. Alih-alih menjadi rumah bagi peradaban, keraton bisa terjebak sebagai panggung drama keluarga.
Dalam konteks yang lebih luas, “ontran-ontran” di Keraton Solo juga menyentuh lapisan lain: politik identitas dan representasi budaya. Setiap kali keraton bergejolak, selalu muncul pertanyaan: siapa yang sebenarnya berhak menafsirkan budaya Jawa hari ini? Apakah bangsawan dengan gelar turun-temurun, atau rakyat yang kini menjadi penjaga nilai-nilai itu melalui praktik keseharian?
Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, kita ingin menghormati warisan. Namun di sisi lain, kita juga menuntut pembaruan. Maka, kisruh di Keraton Solo sebenarnya adalah potret kecil dari pergulatan besar bangsa ini — antara tradisi dan modernitas, antara warisan dan perubahan.
Saatnya Menjadi Teladan Baru
Eko Wiratno pendiri EWRC Indonesia, menilai bahwa konflik ini seharusnya menjadi momentum introspeksi.
“Keraton Surakarta memiliki potensi besar sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif. Tapi selama energinya terkuras untuk perebutan simbol, potensi itu tak akan mekar,” ujarnya kepada Jaringan Arwira Media Group, Kamis(13/11/2025).
Apa yang dikatakan Eko Wiratno punya makna mendalam. Keraton bukan hanya rumah bagi masa lalu, tapi seharusnya juga mercusuar masa depan. Ia bisa menjadi tempat bertemunya tradisi dan inovasi — ruang di mana seni, pariwisata, dan pendidikan budaya berkembang bersama. Tapi itu hanya mungkin jika para pemegang warisan mau bersatu, bukan saling menegasikan.
Kini, saat mata publik tertuju ke Solo, dunia sedang menunggu apakah para pewaris Mataram akan memilih jalan ruwet atau jalan damai. Satu hal pasti: sejarah akan lebih menghormati mereka yang memilih kebijaksanaan daripada kebanggaan kosong.
Karena sejatinya, tahta hanyalah simbol. Tapi makna yang melekat padanya adalah cerminan karakter bangsa.
Dan ketika ontran-ontran akhirnya mereda, semoga yang tersisa bukan luka dan dendam, melainkan kesadaran baru — bahwa budaya hanya akan hidup jika dijaga dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.(**)
Related Posts

10 Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2025: Merekam Jejak Bangsa, Menyatukan Sejarah

Tidur: Disiplin yang Dilupakan dalam Budaya Produktivitas Modern oleh Eko Wiratno(EWRC Indonesia)

BUKU ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Disusun dalam 8 BAB

Diskusi Buku “Prahara di Garis Merah” Ungkap Sejarah Kekerasan 1965 di Klaten dan Boyolali

Eko Wiratno Apresiasi PCM Jatinom dan PRM Krakitan: Bukti Dakwah Muhammadiyah Tak Pernah Padam

No Responses